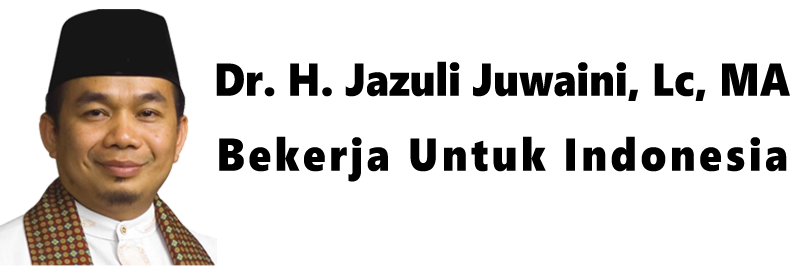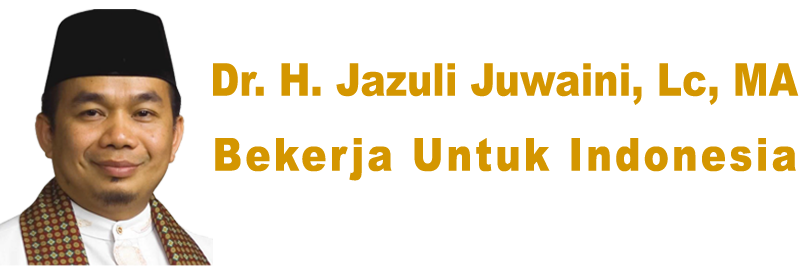Koran SINDO
Sabtu, 11 Januari 2014 − 06:32 WIB

JAZULI JUWAINI
MEKANISME pemilihan kepala daerah menjadi isu yang paling hangat didiskusikan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR RI.
Pemerintah dan sejumlah kalangan Dewan menghendaki perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung atau melalui mekanisme perwakilan sebagaimana langgam yang pernah berlaku pada Orde Baru. Namun, ada juga pihak yang tetap ingin mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat pada setiap tingkatan pilkada.
Ada tiga opsi yang berkembang dalam pembahasan mekanisme pemilihan kepala daerah. Opsi pertama, tetap sebagaimana yang berjalan saat ini, pemilihan kepala daerah langsung untuk provinsi dan kabupaten/ kota.
Opsi kedua, pemilihan kepala daerah langsung untuk provinsi dan mekanisme perwakilan (dipilih DPRD) untuk kabupaten/kota. Opsi ketiga, mekanisme tidak langsung (dipilih DPRD) untuk provinsi dan pemilihan kepala daerah langsung untuk kabupaten/ kota.
Opsi pertama didasarkan pada argumentasi umum bahwa pemilihan langsung oleh rakyat lebih menjamin keterwakilan rakyat dan sehingga lebih tinggi derajat demokratisnya karena setiap suara rakyat bernilai dalam proses sirkulasi kepemimpinan daerah (one person one vote one value).
Menjadi mundur (set-back) secara demokrasi jika deliberasi hak pilih rakyat ditarik kembali atas alasan apa pun karena hak memilih merupakan hak dasar rakyat dalam demokrasi dan ini sudah menjadi komitmen pasca reformasi.
Sementara itu, opsi kedua dan ketiga menghendaki mekanisme pemilihan kepala daerah diubah (dikembalikan) melalui mekanisme perwakilan, hanya bedanya pada tingkat mana mekanisme perwakilan diberlakukan. Argumentasi utama dua opsi ini: Pertama, untuk tujuan efisiensi anggaran negara dalam penyelenggaraan pilkada.
Semua mafhum bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung menyedot anggaran negara/daerah yang sangat besar vis a vis kapasitas anggaran negara/ daerah untuk pembangunan. Kedua, untuk tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikaitkan dengan konseptual titik tekan otonomi dan koordinasi antartingkat pemerintahan daerah.
Konsekuensi dari tiap-tiap kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat mereka merasa memiliki legitimasi riil dari rakyat, yang dalam banyak kasus menyulitkan koordinasi oleh tingkat pemerintahan di atasnya.
Terungkap sejumlah kasus betapa sulitnya gubernur sebagai kepala daerah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan koordinasi dengan bupati dan wali kota di wilayahnya. Bupati dan wali kota “membangkang” terhadap instruksi gubernur bahkan pemerintah pusat cq Kementerian DalamNegeri. Rapat-rapat koordinasi oleh gubernur acapkali sepi dari kehadiran bupati dan wali kota dan hanya diwakili setingkat kepala dinas atau kepala biro yang juga tidak memiliki kewenanganmengambilkebijakan.
Di lain pihak dalam kerangka pelayanan publik dan administrasi pemerintahan daerah, ujung tombak pelaksana pelayanan publik dan administrasi ada pada pemerintahan kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang sejatinya pemerintah provinsi hanya memiliki dan melaksanakan kewenangan pemerintahan lintas kabupaten/kota.
Ini menjadi materi diskusi perihal di mana sebenarnya letak titik tekan otonomi yang kemudian menghadirkan dasar argumentasi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat lazim dilaksanakan pada daerah yang menjadi titik tekan (lokus) otonomi daerah.
Pilkada langsung tetap pilihan terbaik
Penulis ikut serta dalam diskursus dan pembahasan RUU Pilkada di DPR dalam kapasitas sebagai anggota Komisi II memiliki pandangan dan pendapat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pilkada) sebagaimana langgam yang berjalan pasca reformasi tetap merupakan pilihan terbaik: terbaik bagi rakyat, bagi kemajuan demokrasi, serta bagi proses pembangunan daerah dalam kerangka otonomi. Pada posisi ini penulis ingin menyanggah argumentasi pihak yang mengusulkanpemilihankepaladaerah melalui perwakilan.
Pertama, capaian terbesar reformasi politik sejak 1998 adalah pemulihan dan penguatan peran dan partisipasi rakyat dalam proses politik dan kebijakan. Pemilihan umum adalah pengejawantahan demokrasi yang diperjuangkan melawan tirani dan otoritarianisme Orde Baru.
Dalam konteks ini pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sejatinya kritik terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa Orde Baru yang dinilai mengebiri dan memanipulasi suara rakyat.
Kalau saat ini kita kembali pada mekanisme lama, sama saja dengan set-back atau kemunduran demokrasi. Argumentasi efisiensi terbantahkan dengan harga yang harus dibayar dari set-back demokrasi itu. Atas nama efisiensi mengorbankan capaian demokrasi dan penguatan peran dan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi.
Kendati demikian, kita juga tidak perlu menutup mata atas permasalahan dan kelemahan pelaksanaan pilkada selama ini yang harus kita perbaiki dengan menyempurnakan perangkat regulasi, meningkatkan kesadaran para aktor, dan menegakkan hukum dan aturan secara konsekuen.
Bukan dengan menegasi mekanisme demokratis ini dan kembali pada langgam pemilihan (perwakilan) yang juga tidak menjamin demokrasi itu sendiri.
Kedua, argumentasi pemilihan kepala daerah tidak langsung dikaitkan dengan tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (fungsi koordinasi dan lokus otonomi) juga bukan alasan yang sepenuhnya tepat. Penulis berpendapat bahwa hambatan fungsi koordinasi dan supervisi antartingkat pemerintahan bukan disebabkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Ini semata-mata berkenaan dengan manajemen pemerintahan (menyangkut proses dan kualitas kebijakan publik serta kapabilitas dan profesionalitas kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan).
Penulis yakin jika manajemen pemerintahan daerah dilaksanakan secara profesional, jujur dan berintegritas, serta dalam rangka pelaksanaan program-program yang berkualitas, tidak ada alasan dan ruang bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terkendala friksi masalah.
Jika pola koordinasi dan supervisi dilaksanakan atas dasar kepentingan rakyat, tidak ada alasan bagi masing-masing tingkat pemerintahan daerah untuk lari dari tanggung jawab. Penulis justru menduga hambatan koordinasi dan supervisi terjadi akibat kepentingan politik dan kekuasaan (conflict of interest) dari oknum kepala daerah dan pihak-pihak tertentu yang sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat dan pembangunan daerah sebaliknya mereka yang ingin membangun oligarki kekuasaan di daerahnya.
Di era keterbukaan informasi saat ini sejatinya potensi oligarki kekuasaan itu dapat dikikis habis jika manajemen pemerintahan daerah dijalankan secara profesional, penuh integritas, dan berkualitas.
Kalau nyata-nyata program pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi (baik program pemerintah pusat atau program pemerintah provinsi) berkualitas dan dipahami manfaatnya bagi masyarakat luas melalui strategi publikasi media yang baik, bisa saja pemerintah kabupaten/ kota yang mengabaikan bahkan menghambat program tersebut akan terpojok oleh pemberitaan dan opini media sehingga mendapatkan blacklist dari masyarakat.
JAZULI JUWAINI
Anggota Komisi II DPR RI/ Peserta Program Doktor Manajemen SDM UNJ